Jumat, 07 September 2012
Melirik Krisis Papua Bagian Tengah
Posted by Tabloid Suara LSM Online on 01.43
Papua, (SUARA LSM) - Keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan menjadi persoalan utama di Papua bagian tengah yang sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Sayangnya, jika tak ada pendekatan khusus dan tepat bagi masyarakat, berbagai potensi kawasan itu hanya akan menjadi persoalan baru.
Konflik dan baku tembak di beberapa wilayah Papua, renegoisasi kontrak karya PT Freeport Indonesia, dan kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) H Hillary Clinton yang dimulai hari Senin (3/9) lalu seakan-akan tidak ada hubungan langsung. Namun, masing-masing momentum itu mempunyai keterkaitan dengan masyarakat Papua, khususnya perdamaian, keadilan, dan hak-hak asasi manusia, kemudian kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.
Sekadar mengingatkan saja, ketika Menlu AS Condoleezza Rice berkunjung ke Indonesia, saat itu tengah ada pembicaraan saham cadangan minyak terbesar Indonesia di Blok Cepu. Tidak lama berselang, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Blok Cepu kepada ExxonMobil yang merupakan salah satu perusahaan minyak raksasa milik AS. Kehadiran petinggi AS kali ini mungkin saja akan terbukti keterkaitannya dalam beberapa pekan mendatang. Yang, jelas sejumlah kalangan menilai AS senantiasa selalu mempunyai standar ganda atas wilayah yang terkait kepentingannya, termasuk Papua.
Tulisan ini tidak mengulas satu-demi satu daerah di wilayah Papua bagian tengah yang terdiri dari delapan kabupaten yang tersebar dari Mimika, Deiyai, Paniai, Nabire, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Ulasan umum yang dibuat dalam tulisan ini ditambah dengan pengalaman penulis yang sejak tahun 1997 mengunjungi Papua sehingga bisa membuka perspektif yang lebih menyeluruh. Keterbelakangan, sulitnya akses dan sarana transportasi, pendidikan yang tidak memadai hingga benturan budaya yang perlahan memarjinalkan masyarakat lokal semakin menambah kompleksitas persoalan. Kondisi ini diperparah dengan melorotnya kinerja birokrasi yang tidak ditopang keseriuasan para pimpinan daerah sehingga masyarakat dibiarkan “merana” dan “frustasi”.
Tidak heran jika konflik mudah terjadi dan atas nama keamanan aparat hukum dan keamanan harus turun tangan dengan pendekatan kekerasan.
Sejumlah peneliti dan pemerhati pembangunan, khususnya di Papua, tentu sangat memahami kondisi dan perkembangan di kawasan Papua Tengah.
Masing-masing tentu mempunyai analisis tersendiri, namun dengan solusi yang boleh dikatakan tidak jauh berbeda. Ironi ketimpangan pembangunan, salah kelola sumber daya alam (SDA) yang membawa keuntungan segelintir pihak, keterbatasan akses dan sumber daya manusia yang rendah, hingga rasa frustasi dalam ketakberdayaan. Sebagian besar wilayah di Papua Tengah, mempunyai potensi SDA yang cukup bagus, sekalipun belum begitu banyak dikelola. Neles Tebay, doktor jebolan Universitas Kepausan Urbaniana, Roma, Italia, yang sehari-harinya adalah pastor dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Fajar Timur ini, menganalisis sesuai pengalamannya sebagai putra asal Papua Tengah, tepatnya Kabupaten Nabire. Ada tiga tantangan besar yang dihadapi masyarakat wilayah Papua Tengah, yakni krisis budaya, marjinalisasi, dan rendahnya sumber daya manusia.
Krisis budaya yang terjadi karena masyarakat dibanjiri banyak hal, nilai, dan barang-barang baru bersama orang-orang baru, agama, dan lembaga-lembaga baru. Derasnya pengaruh tersebut tak bisa dibendung sehingga menimbulkan “kebingungan” dalam masyarakat asli.
“Masyarakat belum melihat manfaat dan relevansi dari nilai-nilai budaya yang lama untuk hidup di zaman modern. Pada saat yang sama, orang belum mampu hidup menurut tuntutan yang baru,” ujar Neles dalam diskusi akbar yang digelar Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah (FPPPT), Rabu (29/8) di Timika, Papua.
Kondisi tersebut menyebabkan berbagai tingkatan adaptasi masyarakat. Ada yang berusaha mengambil alih budaya baru tetapi tak berhasil memenuhi tuntutan-tuntutan baru. Ada yang berpegang pada budaya tradisionalnya tetapi tidak melihat manfaat dan relevansinya. Sebagian besar menggunakan hal baru dengan menerapkan pola lama dalam budayanya, sekalipun hal-hal baru menuntut pola-pola baru. Bila orang tak mampu mengatasi perubahan-perubahan budaya itu maka akan terjadi krisis budaya. dan krisis identitas sehingga bisa mengarah pada disorientasi. Generasi yang mengalami krisis identias budaya tak melahirkan orang-orang cerdas dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan.
“Sebaliknya, yang mengalami krisis identitas justru menimbulkan banyak masalah sosial,” ujar Neles.
Selain itu, marjinalisasi masyarakat asli yang terhimpit dari persaingan dengan para pendatang yang memiliki keterampilan yang cukup untuk meraih peluang dan sukses. Kesenjangan yang terus melebar tersebut kemudian semakin diperparah dengan budaya dan dampak dari kehadiran puluhan perusahaan besar di kawasan ini.
Menurut Neles, situasi ini semakin diperparah dengan realitas sumber daya manusia yang sangat rendah sehingga warga Papua, khususnya Papua Tengah, semakin tersisih dari pembangunan. Penjelasan Neles tersebut seakan dibenarkan dengan kondisi ibu Beatrix Pekei, yang sehari-hari memungut biaya toilet di Mini Mall, Timika, sembari menyulam noken (tas tradisional) untuk dijual guna menyambung biaya hidup sehari-hari. Padahal, Beatrix mungkin bisa dikatakan sedikit punya daya juang dibandingkan dengan puluhan ribuan warga asli lainnya yang tersisih dan jauh di pelosok Mimika.
Krisis dan marjinalisasi yang dihadapi masyarakat Papua Tengah tersebut mendorong FPPPT untuk membuka dialog terbuka. Memang banyak kajian dan forum yang cenderung elitis dalam meneropong kondisi Papua Tengah. Namun, diskusi yang digelar FPPPT cukup membuka ruang publik dengan melibatkan perwakilan masyarakat dari berbagai distrik yang terdiri dari komunitas adat, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, pemerintahan kecamatan dan desa, serta para guru yang banyak berkecimpung langsung dengan masyarakat.
Tidak heran jika sekitar 500 peserta membanjiri diskusi di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, selama 29-31 Agustus tersebut berbicara apa adanya dengan khas Papua. Ada yang benar-benar bertanya karena ingin tahu, demikian juga yang belum paham pada sebuah persoalan, ada yang menuntut sejumlah hal terkait kesejahteraan dan keadilan, hingga ada yang emosional karena merasa “dijajah” perusahaan asing dan pemerintah Indonesia. Bahkan, ada juga marah-marah dan berteriak karena tidak diberikan kesempatan untuk bertanya karena waktu yang terbatas. Sesi dialog yang sangat sedikit karena keterbetasan waktu pada materi Deputi I Kemenpolhukam Judy Herianto nyaris menimbulkan kericuhan, namun bisa diatasi setelah adanya pemahaman dari para peserta yang selama ini belum pernah diberi ruang untuk berdiskusi. Setidaknya ruang dialog yang mulai terbuka tersebut menjadi modal awal untuk melihat berbagai persoalan lebih obyektif dalam masyarakat.
Selain Neles dan Judy yang mewakili Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menkopolhukam) karena berhalangan hadir, dialog yang membahas politik, pendidikan, dan ekonomi tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara seperti Deputi Bidang Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Suprayoga Hadi, pakar politik CSIS J Kristiadi, Ketua Kaukus Parlemen Papua Paskalis Kosay, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoram Wamro, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hanny Wijaya, dan praktisi pertambangan Jeffrey Mulyono. Sayangnya, Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Dharmono berhalangan hadir.
Menurut Ketua FPPPT Wilhelmus Pigai, perkembangan masyarakat dan pembangunan yang masih tertinggal jauh di wilayah Papua Tengah mendorong dia bersama sejumlah generasi muda dari kawasan ini untuk membuka dialog dan mencoba menggali solusi atas berbagai persoalan yang ada. Apalagi, keterbelakangan yang terjadi justru di tengah-tengah kelimpahan sumber daya alam yang dikeruk oleh sejumlah perusahaan tambang dunia.
“Keterbelakangan, kemerosotan budaya, dan kemiskinan terus meningkat di wilayah Papu Tengah yang justru memiliki kelimpahan sumber daya alam. Inilah beberapa kegelisahan generasi muda di wilaya ini. Perubahan harus dimulai dari para pimpinan daerah yang ditopang masyarakat dengan keberanian untuk bersatu tanpa melihat kepentingan kelompok, suku dan keluarga saja,” tegasnya.
Wilhelmus yang juga anggota DPRD Kabupaten Mimika, Papua, tersebut sangat berharap adanya sejumlah terobosan yang bisa mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas hidup sejumlah kawasan di Papua Tengah. Salah satu terobosan tersebut adalah keberanian dari pengambil kebijakan untuk mengambil suatu langkah yang tepat dan terukur sehingga dapat memutus mata rantai yang membelenggu masyarakat yang tidak mampu dan belum dapat melepaskan diri dari kondisi yang terjadi.
Harapan yang sama juga disampaikan Philipus Monaweyauw, guru dan tokoh masyarakat asal Distrik Mimika Barat, juga Yulianus Anggaibak dari Distrik Agimuga, serta sejumlah peserta dari berbagai distrik lain di Mimika.
Jika sebagian besar peserta lebih banyak memprotes dan menuntut ketidakadilan pemerintah pusat, pandangan yang sedikti berbeda justru dilontarkan guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hanny Wijaya serta praktisi pertambangan dan pemberdayaan masyarakat Jeffrey Mulyono. Dikatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat harus mempunyai komitmen tinggi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya. Tekad dan kesadaran dari setiap warga atau keluarga itu penting sehingga tidak dicitrakan hanya menuntut tanpa berusaha. Bagi Hanny, kesadaran akan pendidikan dan tekad dari dalam diri setiap warga Papua, terutama orang tua dan para guru, merupakan hal yang sangat penting.
“Hal yang paling mendasar adalah harus dimulai dari setiap pribadi dan warga asli Papua. Pihak-pihak lain dan dukungan yang lain merupakan faktor pendukung saja karena kawasan laindi Indonesia pun mempunyai tantangan yang serupa,” kata Hanny.
Sekalipun, dia mengakui, berbagai tantangan dan persoalan pendidikan di Papua cukup kompleks dan tentunya membutuhkan upaya ekstra dalam memberikan dukungan kepada warga Papua. Seharusnya, berbagai potensi dan kendala yang ada di Papua menjadi pendorong mengejar ketertinggalan melalui pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua, James Modouw mengatakan berbagai upaya terus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pendidikan. Untuk itu, salah satu upaya pendukung pendidikan tersebut adalah meningkatkan alokasi dana pendidikan.
Selama ini, khususnya dana otonomi khusus (otsus) Papua masih minim dialokasikan untuk pendidikan. Padahal, komitmen secara nasional adalah sekitar 20% dari anggaran nasional (APBN) maupun anggaran daerah (APBD).
Seperti diketahui, studi yang dilakukan sebuah lembaga di Papua pada tiga tahun lalu menyebutkan, anggaran untuk sektor pendidikan dari dana otsus hanya berkisar 7%. Dalam RAPBN 2013, Dana Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp13,2 triliun. Angka ini naik Rp1,3 triliun dari pagu APBN-P 2012. Dana sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp 4,3 triliun; Papua Barat Rp 1,8 triliun; dan Aceh Rp 6,1 triliun. Padahal, hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan telah terjadi penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat selama 2002-2010. Dari jumlah dana Rp 19,12 triliun yang diperiksa BPK, sebanyak Rp 4,12 triliun telah terjadi penyimpangan. BPK menemukan pendelegasian pengelolaan keuangan kepada elite lokal sebagai implementasi otonomi ternyata tidak diiringi akuntabilitas yang memadai. Dari sejumlah penyelewengan tersebut, tercatat sebanyak Rp 1,85 triliun didepositokan di Bank Mandiri dan Bank Papua yang ditengarai seharusnya menjadi alokasi untuk pendidikan.
Sebagian besar wilayah dan masyarakat Papua Tengah memang tertinggal dibandingkan daerah lain di Papua dan Papua Barat. Deputi Menteri Bidang Pembangunan Daerah Khusus KPDT Suprayoga Hadi pun mengakui hal tersebut. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan terobosan dalam memberdayakan masyarakat. Sayangnya, berbagai program dan dana yang dikucurkan selama ini seakan tidak efektif dan tidak langsung mengenai sasaran. Korupsi yang merajalela, belanja publik yang sangat minim sekitar 10-20% dari APBD, hingga pendekatan proyek fisik semata yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar, sehingga target pemberdayaan manusia pun nyaris tidak tersentuh. Jika tidak ada langkah khusus dan tepat, lingkaran setan yang ada hanya memperlebar kesenjangan dan frustasi yang bisa saja berbuntut pada konflik sosial yang lebih besar.
Jangan sampai para petinggi RI dan elit negeri ini hanya asyik melakukan negoisasi soal PT Freeport Indonesia karena ada “kue” yang begitu besar, tetapi melupakan masyarakat asli Papua. Demikian juga masyarakat tak sekadar menuntut hak-haknya, tanpa mau berusaha karena sudah terlanjur merasa tidak mampu. (SP)




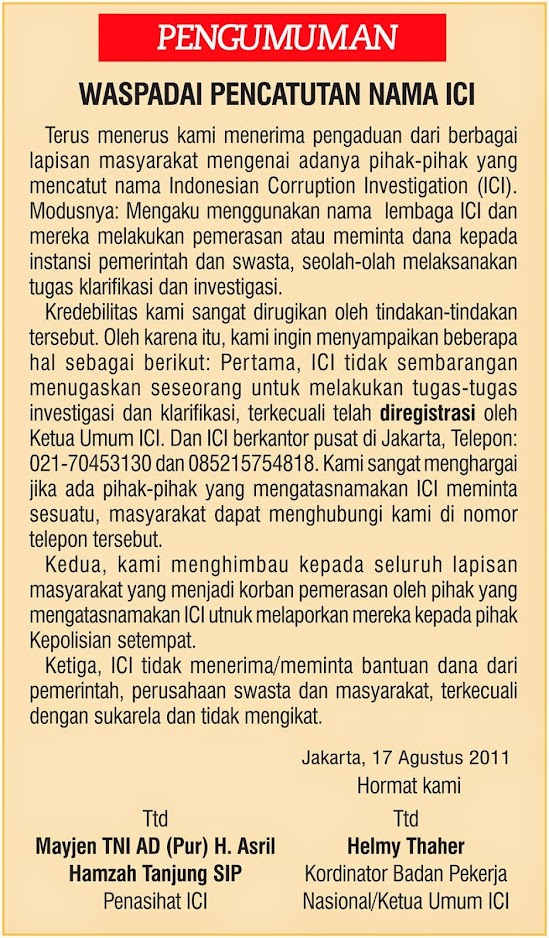











 Jakarta Time
Jakarta Time






1 $type={blogger}:
sedih lihat elit pejabat mengorbankan rakyat papua, di daerah lain juga begitu rakyat dikorbankan
Posting Komentar